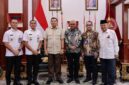ACEH TENGGARA, 23 Desember 2025 — Program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) untuk komoditas kakao yang digelar Dinas Pertanian Aceh Tenggara menuai sorotan. Kegiatan yang disebut bertujuan mendidik petani dalam pengelolaan hama terpadu ini dinilai belum menjawab persoalan mendasar pengelolaan tanaman kakao yang selama ini menjadi komoditas penting di wilayah tersebut.
Kegiatan SL-PHT budidaya kakao itu terpantau berlangsung di perkebunan milik warga, dengan melibatkan sejumlah petani dari beberapa kecamatan. Dari informasi yang dihimpun, program ini dilaksanakan melalui dua gelombang, masing-masing selama lima hari, dengan jumlah peserta per pertemuan sekitar 35 petani.
Namun, minimnya peserta dan luas jangkauan kegiatan, berbanding kontras dengan besaran anggaran yang dialokasikan melalui belanja daerah. Kegiatan ini tercatat menggunakan anggaran mendekati Rp600 juta. Hal ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan pemerhati pertanian setempat mengenai efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik.
Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara menjelaskan bahwa SL-PHT merupakan bagian dari upaya memulihkan produktivitas kakao yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan akibat serangan hama dan penyakit tanaman. Melalui program ini, para pekebun diberikan pemahaman teknis tentang pengendalian hama terpadu sekaligus strategi peningkatan hasil panen.
Namun di lapangan, program ini belum menunjukkan dampak yang signifikan. Masih banyak petani yang mengeluhkan tingginya tingkat serangan hama dan lemahnya produktivitas kebun kakao mereka. Kondisi ini membuat sebagian petani mulai beralih ke tanaman lain yang dinilai lebih tahan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman dan memiliki nilai jual stabil.
“Dulu kakao jadi andalan di sini, tapi sekarang banyak yang tebang. Harga turun, hama makin menjadi. Sudah capek kami rawat, hasilnya tidak sebanding,” kata Juanda, petani kakao asal Tenembak Alas.
Penurunan sentra kakao di sejumlah kecamatan menandai adanya pergeseran prioritas komoditas. Beberapa petani bahkan sudah mulai mengganti lahan mereka menjadi tanaman hortikultura dan palawija lain. Sementara itu, belum ada pendekatan sistematis dalam penyelamatan komoditas kakao berbasis kebijakan yang terintegrasi dengan tata niaga dan teknologi pendamping.
Pengamat pertanian di daerah ini menilai bahwa program seperti SL-PHT membutuhkan evaluasi ketat, utamanya dalam hal distribusi manfaat program, metoda pelatihan, serta keberlanjutan pascapelatihan. Kegiatan penyuluhan—apalagi dengan biaya besar—diharapkan tak hanya simbolis atau sekadar menggugurkan kewajiban anggaran, tetapi mampu menjadi motor penggerak revitalisasi tanaman kakao di tingkat tapak.
Aceh Tenggara selama ini dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi besar dalam produksi kakao, dengan iklim dan kondisi geografis yang mendukung. Namun ketidakseimbangan antara dukungan teknis, intervensi pasar, serta ketahanan petani menghadapi perubahan, menjadi tantangan utama yang perlu dijawab dengan strategi lebih dari sekadar pelatihan singkat.
Dengan tantangan sektor perkebunan yang semakin kompleks, efektivitas setiap program pembangunan perlu ditakar secara sungguh-sungguh. Tanpa penguatan kelembagaan petani, jaminan harga pasar, serta pengendalian hama yang terintegrasi secara nyata, revitalisasi kakao di Aceh Tenggara dikhawatirkan hanya akan menjadi deretan wacana tanpa hasil konkret.
Laporan : Salihan Beruh